Merupakan pihak yang paling berkompeten memegang kekuasaan dalam setiap sistem politik. Pandangan ini dianut pula oleh Max Weber (Gerth dan Mills, 1946) dan atas dasar itu pula Weber dikritik diawal abad 20 oleh mereka yang menganggap bahwa birokrasi sesungguhnya adalah salah satu bentuk organisasi pengaturan yang bisa saja digantikan oleh bentuk pengaturan yang lain. Bagi Weber, pendapat yang menyamakan sosok pejabat dengan sosok penguasa sulit dimengerti dan tidak sesuai dengan kenyataan. Lebih lanjut Weber berpendapat bahwa para pejabat itu lebih merupakan aparat pelaksana yang tidak seharusnya memangku kekuasaan. Dalam masyarakat moderen peran mereka lebih didasarkan pada kekuasaan "legal" ketimbang kekuasaan "karismatik" atau unsur-unsur lain yang lebih bersifat tradisional. Karena itu, wewenang mereka pun senantiasa terbatas dan batas-batas itu harus senantiasa diketahui dan ditegakkan secara jelas, balk melalui hukum-hukum tertulis seperti statuta, peraturan administratif atau pengawasan pengadilan. Di mata Weber, birokrasi adalah bentuk organisasi terbaik untuk menerapkan wewenang legal. Kalau wewenang legal membutuhkan suatu pemerintahan berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan preferensi manusia", maka birokrasi bisa dianggap sebagai "suatu organisasi posisi/ jabatan, dan bukan organisasi manusia". Jadi, organisasi birokrasi terdiri dari sejumlah jabatan atau instansi yang kekuasaan dan tugasnya didefinisikan secara jelas, demikian pula dengan segenap kegiatan dan cakupan wewenangnya. Semuanya bersifat hirarkis dan terpadu menjadi satu kesatuan. Birokrasi akan berjalan dengan baik, jika pengisian jabatan didasarkan pada kemampuan yang bisa dikriteriakan dengan diploma, ujian atau kualifikasi profesional lainnya. Gaji dan struktur karir juga harus diatur secara pasti karena hal itulah yang menjadi satu-satunya mata rantai personal antara jabatan dengan orang-orang yang mengisinya. "Pemerintahan oleh para pejabat" dan "salah satu bentuk organisasi" merupakan dua aspek yang berlainan dari birokrasi. Namun keduanya juga berkaitan, dan sebagaimana yang diperlihatkan oleh sejarah, definisi yang satu merupakan reaksi terhadap definisi yang lain. Jadi kedua aspek tersebut dapat dipadukan dan tidak harus dipertentangkan. Weber, misalnya, nampaknya lebih tertarik pada aspek "pemerintahan oleh para pejabat". Ini dikarenakan, menurut Weber, anggapan itu haruslah dipegang terlebih dahulu sebelum kita dapat menyadari keberlakuan aspek lainnya, yakni gagasan yang menyatakan bahwa birokrasi adalah salah satu bentuk organisasi pemerintahan. Namun sebaliknya, kalau kita terpaku pada aspek kedua, maka kita tidak bisa membayangkan keberlakuan aspek pertama. Artinya, masih menurut Weber, kalau kita terlanjur mengartikan birokrasi sebagai salah satu bentuk organisasi pemerintahan maka sulit bagi kita untuk mengartikan birokrasi itu sebagai "pemerintahan oleh para pejabat". Ia mengatakan: Dalam kondisi-kondisi normal, posisi kekuasaan dari suatu birokrasi yang telah berkembang dengan balk senantiasa kompleks. Para politisi berbakat akan menemukan posisi bagi din i mereka dalam struktur tersebut yang juga akan diisi oleh para ahli profesional atau teknokrat yang memiliki keterampilan terlatih dalam manajemen administrasi. Mereka semua akan sating berbagi tempat agar birokrasi itu dapat melayani masyarakat, yang wahana institusionalnya bisa dijelmakan sebagai sebuah parlemen, presiden yang dipilih langsung, penguasa absolut atau keturunan, atau bisa pula berupa monarki "konstitusional".
Para ilmuwan sosial lainnya yang pada dasarnya menerima definisi birokrasi dari Weber memusatkan perhatian mereka pada berbagai aspek mulai dari kekuasaan birokrasi itu sampai resiko inefisiensinya sebagai sebuah organisasi. Robert Merton (1952), misalnya, melihat bahaya yang terkandung dalam setiap organisasi yang memiliki wewenang pemerintahan, yakni kecenderungan orang-orang yang ada di dalamnya akan melayani kepentingan mereka sendiri dan mengacaukannya dengan fungsi pelayanan yang harus diembannya sehingga membuat mereka enggan mengadakan perubahan-perubahan yang diperlukan. Sementara itu Michel Grozier (1964) Menggambarkan birokrasi sebagai suatu organisasi yang tidak dapat mengoreksi perilakunya berdasarkan kesalahan-kesalahan yang telah dibuatnya".
Michael Nelson Rhodes College Beferensi Albrow, M. (1970) Bureaucracy, New York. Crozier, M. (1964) The Bureaucratic Phenomenon, London. Gerth, H. dan Mills. C.W. (1946) From Max Weber: Essays in Sociology, New York. Laski, H. (1930) 'Bureaucracy dalam Encyclopaedia of the Social Sciences, volume 3, New York dan London. Laswell, H.D. dan Kaplan, A. (1950) Power and Society: Framework for Political Inquiry New Haven, CT. Merton. R. (1952) 'Bureaucratic structure and personality', dalam R. Merton (ed.) Reader in Bureaucracy, Glencoe, IL. Michaels, R. (1962 [19111) Political Parties, New York. Lihat juga: government; management theory; public admi-nistration; public management; Weber. Max Burke, Edmund (1729-97) Edmund Burke adalah negarawan dan teorisi politik Inggris yang lahir di Dublin pada tahun 1729. Ia datang ke London di tahun 1750 dan segera memperoleh reputasi sebagai seorang filsuf dan sastrawan. Di tahun 1765 ia terpilih sebagai anggota majelis rendah dan bertindak sebagai sekretaris partai dan salah satu tokoh penggagas Partai Whig yang saat itu dipimpin oleh Marquis of Rockingham. Ia banyak menulis, antara lain tentang pandangan-pandangannya mengenai berbagai kemungkinan politik. Meski-pun tidak semua gagasannya terwujud, apa yang dikemukakannya itu merupakan sumbangan penting bagi pemikiran politik di masa itu. Pemikiran Burke antara lain tertuang dalam karyanya yang berjudul Reflections on the Revolution in France (1790) dan beberapa karya lainnya di mana ia mengkritik revolusi itu yang oleh partainya sendiri justru disambut sebagai langkah pembebasan dari Absolutisme Bourbon. Karena itu Burke pernah dituduh menghianati prinsip kemerdekaan, dan Burke membela dini dengan menyatakan bahwa konsistensi adalah nilai tertinggi dalam politik. Hal ini dikemukakannya dalam Appeal from the Old to the New Whigs. Ketika membela perjuangan kemerdekaan koloni-koloni Amerika, ia manyatakan bahwa hal itu didasarkan pada dukungannya pada setiap gerakan yang mengibarkan bendera kebebasan. la mengatakan bahwa penduduk Amerika itu mengangkat senjata hanya untuk satu tujuan yakni menolak pajak yang hendak dipaksakan Inggris (Burke, 1855, Appeal, vol. 3). Konsistensi politik nil harus didasarkan pada kondisi yang ada dan tidak bisa begitu saja diturunkan dari prinsip-prinsip baku.
Dalam perbandingan antara kenyataan historis dan prinsip-prinsip abstrak itulah Burke menafsirkan tantangan yang dihadapi oleh kaum revolusioner di Perancis. Menurut Burke, kaum revolusioner Perancis itu adalah para politisi amatir yang mencoba mengatasi berbagai persoalan kompleks dalam masyarakat Perancis dengan seperangkat teori yang disebutnya dengan "hak-hak metafisik". Mereka percaya bahwa suatu konstitusi rasional ideal yang melandasi terciptanya sebuah republik, akan menjamin hak-hak kemanusiaan yang cocok untuk semua masyarakat. Keyakinan inilah yang menurut Burke membangkitkan prasangka dan kepercayaan yang nyaris tahyul mengenai hal-hal serba ideal sehingga mereka terdorong untuk menganggap bahwa semua bentuk pemerintahan yang sudah ada senantiasa korup, tidak adil dan harus dienyahkan. Ketergesa-gesaan inilah yang oleh Burke dikecam. Namun sayang pandangan jemih Burke ini ditafsirkan secara keliru oleh rekan-rekannya sendiri. Burke mengingatkan bahwa kondisi di masyarakat tidaklah hitam putih sehingga setiap upaya penilaian terhadapnya hams senantiasa dilakukan secara hati-hati, dan apa yang sudah ada belum tentu lebih buruk dibandingkan dengan apa yang hendak diciptakan. Masyarakat merupakan suatu pabrik sentimen yang sangat rumit; sekali saja tatanannya rusak, akan sangat sulit diperbaiki. Burke bahkan berpendapat bahwa kaum revolusioner bertindak tanpa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan revolusioner yang sesungguhnya, dan pada akhimya mereka akan terjebak ke dalam kekerasan gelombang teror yang tidak habis-habisnya. Kalau ini terjadi. maka Burke meramalkan bahwa yang akan tercipta nantinya hanyalah kediktatoran militer (dalam kasus Revolusi Perancis ramalan itu memang terbukti). Kajian jenius Burke dalam memecah antitesis konvensional mengenai politik baru dipahami kemudian. Seperti yang ditulisnya sendiri, dirinya bukanlah "teman atau musuh republik atau monarki mana pun dalam bentuk abstrak" (Burke, 1855, Appeal, vol. 3), dan penolakan untuk ber-pihak ini selanjutnya menjadi warna utama dalam aliran konservatisme. Kunci kebijaksanaan politik tidaklah terwujud sebagai pengagung-an prinsip-prinsip serba ideal namun pada sikap jernih yang rendah hati. Sikap jernih seperti itu biasanya tercipta dengan sendirinya berdasarkan pada pengalaman.
Burke menyatakan bahwa, hak terpenting manusia adalah hak untuk dibatasi oleh hukum-hukum yang tepat. Burke juga berpendapat bahwa masyarakat dan pengaturannya sesungguhnya merupakan suatu kontrak, namun kontrak itu haruslah senantiasa diperbaharui dan disesuaikan dengan situasi yang ada. Pandangan dasar inilah yang merupakan kontribusi penting Burke terhadap pemahaman politik. Lebih jauh, Burke menerapkan doktrin-doktrin empiris dalam politik yang dianggapnya lebih dekat dengan kenyataan ketimbang apa yang diduga oleh para filsuf. Pendapatnya mengenai prasangka bertolak dari rasionalisme superfisial para penentangnya yang adakalanya nampak jelas sebagai endemi irrasionalisme yang melanda pemikiran konservatif. Pendapat Burke tersebut berkaitan dengan hubungan antara logika dan nafsu seperti yang dirumuskan oleh Hegel meskipun hal itu dinyatakannya dalam ideom yang berbeda. Penelitian politik Burke merupakan modifikasi konservatif terhadap kondisi politik Inggris dan mencakup banyak bidang. Burke berpendapat bahwa majelis rendah bukanlah semacam konggres para duta besar dari daerah-daerah yang mereka wakili. Rumusannya mengenai kedudukan partai-partai dalam politik Inggris juga merupakan sumbangan penting terhadap diterimanya dan berkembangnya pemerintahan partai, meskipun cakupannya dalam praktek lebih terbatas dari yang diinginkannya (Brewer, 1971). Ketika menghadapi kritikan Warren Hastings, ia menekankan pentingnya perwalian kekuasaan dan kepemilikan yang memang tidak pernah lepas dari pemikirannya. Hanya saja dalam semua tulisan politiknya, Burke mengemukakan pendapatnya dalam berbagai gaya sehingga agak sulit menarik generalisasi terhadapnya. Ambisi pribadi Burke yang terkadang mendorongnya melakukan berbagai manuver dalam dunia politik abad 18 yang sangat kompleks itu mendorong sejumlah penulis (misalnya Namier 1929; Young, 1943) menganggapnya tidak lebih dari seorang oportunis berlidah tajam. Terlepas dari itu, apa yang dikemukakan Burke tetap diakui merupakan kontribusi penting dalam perkembangan pemikiran politik.
birokrasi dan peraturan administratif atau pengawasan pengadilan



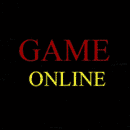
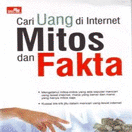












Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.